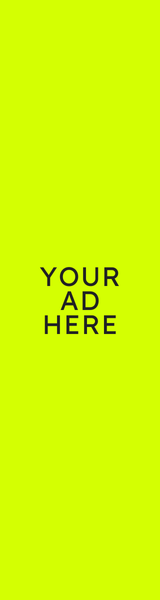Jakarta,CentangSatu.com -|Di sebuah ruang konferensi di Jakarta, awal Oktober 2025, denting nada dan suara manusia beradu dengan gema algoritma. Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 bukan sekadar forum tahunan, tapi seperti panggung kecil tempat masa depan musik Indonesia sedang diuji: masihkah manusia memegang kendali, atau sudah waktunya berbagi dengan mesin?
Selama empat hari, 8–11 Oktober, ratusan pelaku musik, regulator, dan penggerak industri berkumpul di bawah tema yang menggugah: “Musik di Masa Depan: Harapan dan Ancaman.”
Harapan karena teknologi menjanjikan efisiensi, distribusi luas, dan akses tanpa batas. Ancaman karena di balik layar digital, ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah rasa bisa dikodekan?
Nada-nada dari Mesin dan Jiwa
Dalam pidato kuncinya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, memulai dengan nada yang tegas tapi reflektif.
“Kita sedang hidup di era di mana disrupsi digital—terutama kecerdasan buatan—masuk begitu dalam dan mengguncang seluruh sendi kehidupan,” ujarnya.
AI, katanya, kini mampu menciptakan lirik, melodi, bahkan harmoni. Tapi, ia cepat menambahkan sesuatu yang membuat ruangan itu kembali sunyi.
“Musik merekam emosi manusia ke dalam nada-nada. Mesin mungkin bisa meniru, tapi tidak bisa menggantikan getarannya.”
Ada semacam peringatan lembut di situ — bahwa di tengah semua inovasi, manusia jangan sampai kehilangan pusat gravitasi kreatifnya.
Nezar juga menyebut pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan buatan nasional, di mana industri musik menjadi salah satu fokus. Bukan untuk mengontrol kreativitas, melainkan untuk menata ruangnya agar tetap adil.
“Kita ingin inovasi berjalan seimbang, sambil tetap menjaga hak dan integritas para seniman,” tegasnya.
Diskusi yang Berdenyut
Panel diskusi yang dipandu oleh Willy Winarko seolah menjadi orkestra pemikiran. Lima panelis hadir dengan suara dan sudut pandangnya masing-masing: Gerhana Sasongko (Kementerian Komunikasi dan Digital), Hastaviyasa (Langit Musik), Morin Chandra (ASIRI), Miftah Faridh Oktofani (Sosialoka Indonesia), dan Christian Bong (Indomusikgram).
Gerhana berbicara dari sisi kebijakan. Ia percaya bahwa masa depan hanya bisa dihadapi dengan kesiapan digital. “Kita tidak bisa menolak perubahan, tapi kita bisa mempersiapkan diri,” katanya.
Dari sisi platform, Hastaviyasa dan Miftah Faridh berbagi realita lapangan: algoritma memang membantu, tapi juga bisa menelan. “Ancaman itu pasti ada bagi yang tidak mampu beradaptasi,” kata Miftah, “sisanya adalah tantangan. Kita harus riding the wave.”
Sementara Morin Chandra, mewakili Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), menyoroti hal paling mendasar—apresiasi terhadap musik itu sendiri.
“Revenue kita bisa besar, tapi apresiasi terhadap musik masih terbatas. Padahal, setiap nada layak dihargai.”
Dan di antara semua suara itu, Christian Bong dari Indomusikgram menutup dengan refleksi yang menggugah.
“Teknologi akan terus berganti, tapi musik akan selalu menemukan tempatnya di hati para pendengar yang semakin inklusif.”
Kolaborasi: Kunci yang Tak Bisa Digantikan
Ketika panel berakhir, satu hal terasa jelas: AI bukan musuh, tapi cermin. Ia memaksa industri musik untuk berevolusi, tapi juga untuk kembali melihat siapa dirinya.
Kementerian Kebudayaan berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pijakan baru — bukan hanya untuk menghadapi tantangan, tapi juga untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Di masa depan, ketika algoritma semakin canggih, yang paling dibutuhkan bukan lagi sekadar teknologi, melainkan ekosistem yang manusiawi.
Karena pada akhirnya, musik bukan tentang seberapa pintar mesin menciptakan nada, tetapi tentang bagaimana manusia terus menemukan dirinya di antara bunyi.